(11) The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia
Penerbit: Ithaca: Cornell University Press (1973)
FEITH terpikat oleh Indonesia muda yang memilih demokrasi liberal-cita-cita yang, menurut dia, digencet dari dua sisi: militer dan "pemimpin orator". Pada Desember 1949-Maret 1957, periode politik yang ia teliti, ada dua tipe pemimpin, yakni ahli pemerintahan dan pemimpin massa.
Ahli pemerintahan, menurut Feith, berkemampuan hukum, teknis pemerintahan, dan fasih berbahasa asing. Mereka sangat mengutamakan pembangunan ekonomi serta tak menolak tenaga dan modal asing. Adapun pemimpin massa ahli membakar gelora massa, pandai memberi harapan tapi tak cakap mewujudkannya. Semakin lama, Indonesia dikuasai pemimpin massa.
Adnan Buyung Nasution, pakar hukum, menganggap Feith terlalu mencampur konsep kenegaraan dengan Soekarno dan Hatta-pasangan pemimpin massa dan ahli pemerintahan. Dulu, kata dia, Indonesia menerapkan sistem dwitunggal yang membuat kacau. Padahal demokrasi tak bergantung pada orang per orang.
(12) Dualistische Economy Penerbit: Leiden: Van Doesburgh (1930)
SELAIN sistem ekonomi "impor", yakni kapitalisme modern, di Asia berkembang sistem ekonomi tradisional. Kedua sistem ini mustahil bercampur. Boeke menganggap perlu teori ekonomi khusus untuk masyarakat yang menganut dua sistem ini.
Gumilar Rusliwa Somantri, sosiolog dari Universitas Indonesia, menilai cara pandang Boeke menarik. Tapi ia menganggap ada kesalahan persepsi bahwa sektor informal tak adaptif dengan sistem kapitalistik. Padahal kapitalisme di banyak negara di Asia adalah kapitalisme kecil.
(13) Seni Lukis, Kesenian, dan Seniman Penerbit: Yayasan Aksara Indonesia, Yogyakarta (2000)
PELUKIS Soedjojono (1913-1986) menyunting setiap tulisan yang ia susun pada 1930-1945. Buku ini terbit bersamaan dengan agresi militer Belanda, ketika para seniman ikut hijrah ke Yogyakarta. Isinya berkisar tentang seni rupa dan nasionalisme.
Mia Bustam, 88 tahun, istri pertama Soedjojono, menganggap mantan suaminya "seorang nasionalis yang tak tertutup pada internasionalisme". Jim Supangkat, kurator independen, menilai Soedjojono mengangkat tema nasionalisme yang mengandung universalisme.
(14) Nationalism and Revolution in Indonesia Penerbit: Cornell University Press (1952)
KAHIN beruntung berada di Indonesia saat negeri ini muda. Sejak pertengahan 1948 hingga setahun kemudian, ia mengamati langsung pergulatan tokoh-tokoh Republik dalam menegakkan kemerdekaan. Guru besar Universitas Cornell, Amerika Serikat, itu dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan Republik Indonesia ke dunia.
Kahin menulis pelopor pergerakan bangsa ialah Raden Ajeng Kartini, bukan dokter Wahidin Soedirohoesodo. Buku ini memancing polemik. Mochtar Pabottingi, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menilai buku ini menangkap semangat bangsa menjelang 1950-an.
(15) Indonesian Political Thinking: 1945-1965 Penerbit: Ithaca, New York (1970)
FEITHh dan Castles menyimpulkan ada lima aliran pemikiran politik di Indonesia hingga 1965: Islam yang direpresentasikan Partai Nahdlatul Ulama dan Masyumi, sosial demokrasi, tradisionalisme Jawa, nasionalisme radikal yang diwakili Partai Nasionalis Indonesia, serta komunisme dengan ikonnya, Partai Komunis Indonesia. Tiga di antaranya masih bertahan hingga kini: Islam, tradisionalisme Jawa, dan nasionalis.
(16) The Religion of Java Penerbit: The University of Chicago Press, Chicago, dan The University of Chicago, Ltd., London (1960)
CLIFORD Geertz paham betul tradisi dan kebudayaan multikultural masyarakat Jawa. Sejak 1959, ia dan lima rekan penelitinya melakukan riset di sebuah kota yang disamarkannya menjadi Pare. Kota kecil di Jawa Timur ini dipilih karena menggambarkan budaya Jawa yang tidak dipengaruhi Keraton Yogyakarta dan Solo.
Masyarakat Jawa terbagi menjadi kelompok abangan, santri, dan priyayi. Penggolongan ini dikritik keras Harsya Wardana Bachtiar melalui The Religion of Java: A Commentary (1973), yang menganggap priyayi seharusnya tak masuk klasifikasi. "Tulisan Geertz tak lagi cocok dalam konteks sekarang. Masyarakat Jawa mengalami banyak perubahan," kata guru besar antropologi budaya Universitas Gadjah Mada, Heddy Shri Ahimsa Putra.
(17) Netherlands Indie, A Study of Plural Economy Penerbit: Cambridge: At The University Press dan New York: The Macmillan Company (1944)
INDONESIA adalah sekumpulan anggota masyarakat yang majemuk. Meski hidup berdampingan secara fisik, perbedaan sosial budaya membuat mereka terpisah dan tak tergabung dalam suatu unit politik. Efeknya, timbul perbedaan kelompok ekonomi.
Ada orang Belanda minoritas yang menjadi penguasa, masyarakat Timur asing, terutama Tionghoa, serta pribumi yang cenderung menjadi pelayan di negeri sendiri. Kelompok terakhir secara ekonomi menempati peringkat terbawah.
Menurut ekonom Revrisond Baswier, penelitian sejarawan Inggris itu masih relevan hingga kini. Transformasi ekonomi Indonesia dari zaman kerja paksa sampai sekarang lebih banyak akibat tekanan luar, katanya.
(18) Capita Selecta Penerbit: Bulan Bintang, Jakarta, (jilid I, 1955) dan Pustaka Pendis, Jakarta, (jilid II, 1955), (jilid I)
BUKU ini merupakan kumpulan tulisan, pidato, catatan, dan wawancara Natsir. Tulisan tokoh Masyumi itu di majalah Pandji Islam dan Al-Manar pada 1938-1942 dikumpulkan pada jilid pertama. Memakai nama samaran A. Muchlis, ia menulis kebudayaan dan filsafat, pendidikan, agama, ketatanegaraan, serta persatuan agama dan negara.
Teks pada jilid kedua lebih beragam, merupakan pidato dan wawancara Natsir dengan pers pada 1950-1955, di antaranya pidato di parlemen dan radio.
Pengamat politik Bachtiar Effendi menilai Capita Selecta mencerminkan perhatian utama Natsir terhadap Islam dan negara. "Kata-katanya merupakan perpaduan antara intelektualisme dan seni yang tinggi," katanya.
(19) Indonesia in den Pacific-Kernproblemen van den Aziatischen Penerbit: Penerbit Sinar Harapan (1937)
JURNALIS Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangie memaparkan soal kekuatan, kekuasaan, dan kepentingan di Pasifik. Doktor pertama Indonesia di bidang matematika dan sains ini menganggap posisi Indonesia sangat istimewa.
Budayawan Th. Sumartana menilai Ratulangie sebagai intelektual Kristen pertama yang menghargai makna historis dan kebangkitan Islam di Indonesia. Ia menempatkan Sarikat Islam sebagai wakil kebangkitan seluruh rakyat yang tertindas.
(20) Perubahan Sosial di Yogyakarta Penerbit: Gadjah Mada University Press, 1990
MENTALITAS masyarakat Yogyakarta berubah dari introvert ke extrovert setelah kota itu menjadi ibu kota Republik Indonesia pada 1946-1949. Banyak orang dari berbagai daerah memasuki kota itu, yang membuat masyarakat asli membuka diri. Di situlah muncul kesadaran bahwa pendidikan dapat menjadi jembatan kesuksesan.
(21) Dasar-dasar Pemikiran Tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun Penerbit: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta (1973)
BERISI rangkuman ceramah, diskusi, dan wawancara, buku ini memuat pemikiran Ali Moertopo soal akselerasi pembangunan 25 tahun. Ia menganggap pembangunan dan modernisasi masyarakat seperempat abad setelah kemerdekaan belum juga maksimal.
Ali memaparkan kondisi masyarakat, kekuatan bangsa, dan strategi untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan, menurut dia, berarti perombakan berbagai hambatan kemajuan. Akselerasi pembangunan identik dengan percepatan modernisasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadikan buku ini rujukan untuk menyusun strategi pembangunan jangka panjang.
(22) Manusia dan Kebudayaan di Indonesia Penerbit: Djambatan, Jakarta (1971)
BUKU yang ditulis oleh 13 orang antropolog ini berisi budaya dan adat istiadat pelbagai suku bangsa di Indonesia: Aceh, Nias, Batak, Minangkabau, Jawa, Bali, Kalimantan, Minahasa, Ambon, Flores, Timor, hingga Tionghoa.
Setiap bab menggambarkan satu suku, ditulis seorang ahli dari suku yang sama atau peneliti yang mengunjungi dan meneliti daerah itu.
(23) Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini Penerbit: Alumni, Bandung (1983)
MERUPAKAN kumpulan karangan, pernyataan, dan pidato Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri, buku ini dijadikan pegangan untuk menganalisis pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pergulatan Mochtar memperjuangkan keutuhan teritorial dalam konvensi hukum laut internasional tercatat dalam buku ini. Hasil perjuangan itu sampai kini menjadi sumber hukum kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
(24) Culture and Politics in Indonesia Penerbit: Cornell University Press, London (1972)
UPAYA mengidentifikasi jejak budaya dalam tata politik Indonesia. Para penulisnya mewakili sejumlah ahli antropologi, sejarah, dan ilmu politik. Mereka mengulas cara institusi, kepercayaan, dan nilai-nilai tradisi mempengaruhi kesadaran kekuasaan. Begitu pula pemberontakan, afiliasi politik, yang pada akhirnya membentuk ekspresi budaya baru.
(25) Art in Indonesia: Continuities and Change Penerbit: Cornell University Press, New York (1967)
DALAM buku ini Claire Holt berupaya melacak kontinuitas dan diskontinuitas sejarah kebudayaan Indonesia. Ia menggunakan bahan yang amat luas, mulai data arkeologi sampai relief-relief. Buku ini terdiri atas tiga bagian: warisan, tradisi yang hidup, dan seni modern. Setiap bagian merupakan periode tersendiri dalam sejarah seni Indonesia, dari zaman prasejarah hingga seni rupa Indonesia pada paruh pertama abad ke-20.
Holt (1901-1970) mampu menyajikan argumentasi, ada benang merah yang tak terlihat antara lukisan-lukisan di dinding gua di Pasemah dan lukisan Sudjojono.
(26) Science and Scientists in the Netherlands Indies Penerbit: Board for the Netherlands Indies, Surinam & Curaao, New York (1945)
INILAH buku pepak informasi ilmu alam yang dijadikan panduan ilmuwan Indonesia selepas kemerdekaan. Disusun oleh 75 kontributor, sebagian besar materi sudah pernah dipublikasikan pada 1869-1944. Bentuknya makalah ilmiah, pidato, laporan perjalanan, serta daftar institusi ilmiah dan ilmuwan di Hindia Belanda semasa pendudukan Jepang. Tak kurang dari 134 ilustrasi-foto, sketsa, diagram, dan peta-melengkapi buku ini.
(27) Alam Asli Indonesia: Flora, Fauna, dan Keserasian Penerbit: Yayasan Indonesia Hijau dan Gramedia (1986)
KEKAYAAn flora dan fauna Indonesia dibahas tuntas oleh Kathy MacKinnon, ahli zoologi asal Inggris, dalam buku ini. MacKinnon menelisik keragaman alam Indonesia berdasarkan lokasinya: hutan hujan Kalimantan dan Sumatera, Jawa-Bali, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, serta Papua. Habitat pinggiran semacam bukit kapur, sungai, danau, hutan bakau, tepi pantai, dan karang laut juga dibahas.
MacKinnon mendedikasikan satu bab khusus tentang hubungan manusia Indonesia dengan alamnya. Misalnya bagaimana alam membentuk suku-suku yang berbeda. Kolonialisme dianggap berpengaruh besar karena banyaknya hutan hujan yang beralih menjadi lahan pertanian dan perkebunan.
(28) Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan Penerbit: LP3ES, Jakarta (1981)
MUBYARTO (1938-2005), guru besar Universitas Gadjah Mada, menggagas sistem ekonomi yang mengacu pada etika dan falsafah Pancasila. Sistem ini mengharapkan terwujudnya pemerataan ekonomi dan sosial. Ide utamanya: mendorong para pelaku ekonomi bekerja berdasarkan moral serta mekanisme yang sehat.
(29) NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru Penerbit: LKiS dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994
SEMULA Martin menganggap kaum tradisional sebagai penghambat modernisasi. Setelah mengkaji Nahdlatul Ulama, ia menyimpulkan organisasi "kaum tradisionalis" ini memberikan warna lain dalam proses modernisasi.
Tergambar pula perubahan haluan politik Nahdlatul Ulama: dari semula mengkritik pemerintah, melakukan rekonsiliasi dengan menerima Pancasila sebagai asas tunggal, lalu meninggalkan politik praktis. Sifat paling menonjol dari Nahdlatul adalah sangat terdesentralisasi, yang menggambarkan kemandirian para kiai lokal.
(30) Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban) Penerbit: Yayasan Idayu, Jakarta (1981)
MUNAFIK, segan bertanggung jawab, berjiwa feodal, boros, dan percaya takhayul, tapi berjiwa seni tinggi. Itulah orang Indonesia yang digambarkan buku ini. Naskahnya pertama kali dibacakan Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai ceramah di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 6 April 1977.
Mochtar memaparkan, ciri-ciri itu hasil sekian banyak persinggungan peradaban. Mochtar mengimbau rakyat Indonesia untuk terus mengelola kekayaan nasional, daripada membiarkan diri terbuai jerat kapitalisme.
(31) Catatan Subversif Penerbit: Yayasan Obor Indonesia dan PT Penerbit Gramedia (1987)
INI sebenarnya catatan harian Mochtar Lubis selama sembilan tahun sejak 22 Desember 1956: ketika ia dipenjarakan dan kemudian menjadi tahanan luar. Di situ digambarkan antara lain perilaku elite-elite politik zaman Soekarno dan orang-orang yang dipenjarakan rezim kala itu. Pemimpin Redaksi Indonesia Raya ini juga menulis kasus korupsi pada saat itu.
(32) Pembagian Kekuasaan Negara Penerbit: Aksara Baru (1978)
BERISI teori pembagian kekuasaan negara di Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, serta Indonesia. Buku ini berpengaruh pada proses pembentukan tata negara Indonesia. Pemisahan kekuasaan dalam arti material tak pernah dilaksanakan di Indonesia. Yang ada adalah pemisahan formal.
(33) Laporan dari Banaran Penerbit: Sinar Harapan (1960)
MERUPAKAN memoar Jenderal Simatupang yang dicatatnya selama setahun hingga pengakuan kedaulatan RI, 27 Desember 1949. Di situ diungkapkan peran rakyat dalam perjuangan, termasuk ungkapan Jenderal Sudirman tentang " kemanunggalan rakyat dan tentara". Yang hendak ditonjolkan bukan hanya tentara yang berperan dalam perang rakyat 1945.
(34) Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin Penerjemah: Yusron Asrofie Penerbit: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta (1983)
PROFESOR emeritus Chiba University, Jepang, ini meneliti pergerakan Muhammadiyah di Kotagede, Yogyakarta, 1900-1972. Kotagede dianggap sebagai pusat budaya Jawa yang sinkretis. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam pembaruan ternyata tak bertentangan dengan kebudayaan Jawa. Ini bertolak belakang dengan citra organisasi itu sebagai gerakan pemurnian ajaran Islam. Muhammadiyah justru dianggap terpadu dengan tradisi kejawen dalam menyaring intisari Islam.
(35) Six Decades of Science and Scientists in Indonesia Penerbit: Naturindo, Bogor (2005)
SETELAH 60 tahun Indonesia merdeka, Setijati menggagas buku penerus Science and Scientists in the Netherlands Indies. Pada 2005, berkumpullah 22 peneliti senior, kebanyakan telah pensiun, dan generasi pertama ilmuwan Indonesia. Masing-masing menyusun tulisan dalam bahasa Inggris sesuai dengan bidang keilmuannya.
Beragam topik dalam koridor ilmu alam disajikan, dari geofisika, ilmu tanah, mikrobiologi, ilmu serangga, ornitologi (ilmu burung), nutrisi, kehutanan, pendidikan perbenihan, pengembangan jurnal ilmiah, hingga sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
(37) Pedoman Etik Penelitian Kedokteran Indonesia Penerbit: Fakultas Kedokteran UI (1986)
INI hasil Lokakarya Nasional Etika Penelitian yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 1986. Fakultas itu sebelumnya telah melansir beberapa kode etik penelitian kedokteran, tapi buku ini menjadi rujukan karena disusun dari urun rembuk fakultas kedokteran se-Indonesia.
Meski tipis, buku ini memuat panduan etika penelitian yang padat. Etika penelitian terhadap manusia dan hewan serta penggunaan jenazah diuraikan kerangkanya. Buku ini menyinggung pula etika penulisan ilmiah.
(38) A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia Penerbit: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, Ithaca, New York (1971)LEBIH dikenal sebagai "Cornell Paper", inilah sejarah Gerakan 30 September yang berlawanan dengan versi penguasa Orde Baru. Analisis diambil berdasarkan dokumen Mahkamah Militer Luar Biasa serta artikel-artikel media massa di Jakarta, Medan, Solo, Bali, dan Surabaya pada Oktober-November 1965.
Cornell Paper mengungkapkan, kejadian 30 September 1965 adalah masalah internal Angkatan Darat. Partai Komunis Indonesia justru tidak mengetahui gerakan itu. Naskah yang diedarkan terbatas pada 10 Januari 1966 ini awalnya tanpa nama penyusun. Banyak dikritik karena dianggap kurang akurat, naskah itu langsung memicu perdebatan kalangan intelektual. Identitas penulis akhirnya bocor. Sejak 1968 hingga tumbangnya Orde Baru, Anderson ditolak masuk Indonesia. Pada 1971, edisi revisi naskah itu diterbitkan sebagai buku, lengkap dengan nama penyusunnya.
(39) 125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia 1851-1976 Penerbit: Fakultas Kedokteran UI (1976)
DISUSUN oleh profesor-profesor Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, buku ini merangkum 125 tahun perjalanan pendidikan kedokteran di Nusantara. Pijakan awalnya 1851, ketika Dokter Djawa School, sekolah dokter pertama di Indonesia, didirikan di Jakarta. Penyusun menguraikan perkembangan sekolah dokter pada masa penjajahan Belanda, Jepang, hingga 1976.
Para penulis menyinggung pula kehidupan siswa School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA), cikal-bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Buku ini memuat daftar lulusan pendidikan kedokteran dari zaman Belanda, daftar dokter yang gugur atau hilang semasa perang kemerdekaan, dan statistik mahasiswa kedokteran di Indonesia. l
(40) Ekologi Pedesaan: Sebuah Bunga Rampai Penerbit: CV Rajawali, Jakarta (1982)
BERDASARKAN penguasaan tanah sebagai alat produksi petani, Sajogyo mengelompokkan masyarakat tani sebagai petani atas, tengah, gurem, dan tunakisma. Petani gurem dan tunakisma alias buruh tani merupakan mayoritas masyarakat pedesaan. Tapi mereka tak mendapatkan perhatian politik. Akibat kritiknya, Sajogyo dicopot dari jabatan Ketua Badan Pelaksana Survei Agro-Ekonomi.
Penerbit: Ithaca: Cornell University Press (1973)
FEITH terpikat oleh Indonesia muda yang memilih demokrasi liberal-cita-cita yang, menurut dia, digencet dari dua sisi: militer dan "pemimpin orator". Pada Desember 1949-Maret 1957, periode politik yang ia teliti, ada dua tipe pemimpin, yakni ahli pemerintahan dan pemimpin massa.
Ahli pemerintahan, menurut Feith, berkemampuan hukum, teknis pemerintahan, dan fasih berbahasa asing. Mereka sangat mengutamakan pembangunan ekonomi serta tak menolak tenaga dan modal asing. Adapun pemimpin massa ahli membakar gelora massa, pandai memberi harapan tapi tak cakap mewujudkannya. Semakin lama, Indonesia dikuasai pemimpin massa.
Adnan Buyung Nasution, pakar hukum, menganggap Feith terlalu mencampur konsep kenegaraan dengan Soekarno dan Hatta-pasangan pemimpin massa dan ahli pemerintahan. Dulu, kata dia, Indonesia menerapkan sistem dwitunggal yang membuat kacau. Padahal demokrasi tak bergantung pada orang per orang.
(12) Dualistische Economy Penerbit: Leiden: Van Doesburgh (1930)
SELAIN sistem ekonomi "impor", yakni kapitalisme modern, di Asia berkembang sistem ekonomi tradisional. Kedua sistem ini mustahil bercampur. Boeke menganggap perlu teori ekonomi khusus untuk masyarakat yang menganut dua sistem ini.
Gumilar Rusliwa Somantri, sosiolog dari Universitas Indonesia, menilai cara pandang Boeke menarik. Tapi ia menganggap ada kesalahan persepsi bahwa sektor informal tak adaptif dengan sistem kapitalistik. Padahal kapitalisme di banyak negara di Asia adalah kapitalisme kecil.
(13) Seni Lukis, Kesenian, dan Seniman Penerbit: Yayasan Aksara Indonesia, Yogyakarta (2000)
PELUKIS Soedjojono (1913-1986) menyunting setiap tulisan yang ia susun pada 1930-1945. Buku ini terbit bersamaan dengan agresi militer Belanda, ketika para seniman ikut hijrah ke Yogyakarta. Isinya berkisar tentang seni rupa dan nasionalisme.
Mia Bustam, 88 tahun, istri pertama Soedjojono, menganggap mantan suaminya "seorang nasionalis yang tak tertutup pada internasionalisme". Jim Supangkat, kurator independen, menilai Soedjojono mengangkat tema nasionalisme yang mengandung universalisme.
(14) Nationalism and Revolution in Indonesia Penerbit: Cornell University Press (1952)
KAHIN beruntung berada di Indonesia saat negeri ini muda. Sejak pertengahan 1948 hingga setahun kemudian, ia mengamati langsung pergulatan tokoh-tokoh Republik dalam menegakkan kemerdekaan. Guru besar Universitas Cornell, Amerika Serikat, itu dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan Republik Indonesia ke dunia.
Kahin menulis pelopor pergerakan bangsa ialah Raden Ajeng Kartini, bukan dokter Wahidin Soedirohoesodo. Buku ini memancing polemik. Mochtar Pabottingi, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menilai buku ini menangkap semangat bangsa menjelang 1950-an.
(15) Indonesian Political Thinking: 1945-1965 Penerbit: Ithaca, New York (1970)
FEITHh dan Castles menyimpulkan ada lima aliran pemikiran politik di Indonesia hingga 1965: Islam yang direpresentasikan Partai Nahdlatul Ulama dan Masyumi, sosial demokrasi, tradisionalisme Jawa, nasionalisme radikal yang diwakili Partai Nasionalis Indonesia, serta komunisme dengan ikonnya, Partai Komunis Indonesia. Tiga di antaranya masih bertahan hingga kini: Islam, tradisionalisme Jawa, dan nasionalis.
(16) The Religion of Java Penerbit: The University of Chicago Press, Chicago, dan The University of Chicago, Ltd., London (1960)
CLIFORD Geertz paham betul tradisi dan kebudayaan multikultural masyarakat Jawa. Sejak 1959, ia dan lima rekan penelitinya melakukan riset di sebuah kota yang disamarkannya menjadi Pare. Kota kecil di Jawa Timur ini dipilih karena menggambarkan budaya Jawa yang tidak dipengaruhi Keraton Yogyakarta dan Solo.
Masyarakat Jawa terbagi menjadi kelompok abangan, santri, dan priyayi. Penggolongan ini dikritik keras Harsya Wardana Bachtiar melalui The Religion of Java: A Commentary (1973), yang menganggap priyayi seharusnya tak masuk klasifikasi. "Tulisan Geertz tak lagi cocok dalam konteks sekarang. Masyarakat Jawa mengalami banyak perubahan," kata guru besar antropologi budaya Universitas Gadjah Mada, Heddy Shri Ahimsa Putra.
(17) Netherlands Indie, A Study of Plural Economy Penerbit: Cambridge: At The University Press dan New York: The Macmillan Company (1944)
INDONESIA adalah sekumpulan anggota masyarakat yang majemuk. Meski hidup berdampingan secara fisik, perbedaan sosial budaya membuat mereka terpisah dan tak tergabung dalam suatu unit politik. Efeknya, timbul perbedaan kelompok ekonomi.
Ada orang Belanda minoritas yang menjadi penguasa, masyarakat Timur asing, terutama Tionghoa, serta pribumi yang cenderung menjadi pelayan di negeri sendiri. Kelompok terakhir secara ekonomi menempati peringkat terbawah.
Menurut ekonom Revrisond Baswier, penelitian sejarawan Inggris itu masih relevan hingga kini. Transformasi ekonomi Indonesia dari zaman kerja paksa sampai sekarang lebih banyak akibat tekanan luar, katanya.
(18) Capita Selecta Penerbit: Bulan Bintang, Jakarta, (jilid I, 1955) dan Pustaka Pendis, Jakarta, (jilid II, 1955), (jilid I)
BUKU ini merupakan kumpulan tulisan, pidato, catatan, dan wawancara Natsir. Tulisan tokoh Masyumi itu di majalah Pandji Islam dan Al-Manar pada 1938-1942 dikumpulkan pada jilid pertama. Memakai nama samaran A. Muchlis, ia menulis kebudayaan dan filsafat, pendidikan, agama, ketatanegaraan, serta persatuan agama dan negara.
Teks pada jilid kedua lebih beragam, merupakan pidato dan wawancara Natsir dengan pers pada 1950-1955, di antaranya pidato di parlemen dan radio.
Pengamat politik Bachtiar Effendi menilai Capita Selecta mencerminkan perhatian utama Natsir terhadap Islam dan negara. "Kata-katanya merupakan perpaduan antara intelektualisme dan seni yang tinggi," katanya.
(19) Indonesia in den Pacific-Kernproblemen van den Aziatischen Penerbit: Penerbit Sinar Harapan (1937)
JURNALIS Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangie memaparkan soal kekuatan, kekuasaan, dan kepentingan di Pasifik. Doktor pertama Indonesia di bidang matematika dan sains ini menganggap posisi Indonesia sangat istimewa.
Budayawan Th. Sumartana menilai Ratulangie sebagai intelektual Kristen pertama yang menghargai makna historis dan kebangkitan Islam di Indonesia. Ia menempatkan Sarikat Islam sebagai wakil kebangkitan seluruh rakyat yang tertindas.
(20) Perubahan Sosial di Yogyakarta Penerbit: Gadjah Mada University Press, 1990
MENTALITAS masyarakat Yogyakarta berubah dari introvert ke extrovert setelah kota itu menjadi ibu kota Republik Indonesia pada 1946-1949. Banyak orang dari berbagai daerah memasuki kota itu, yang membuat masyarakat asli membuka diri. Di situlah muncul kesadaran bahwa pendidikan dapat menjadi jembatan kesuksesan.
(21) Dasar-dasar Pemikiran Tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun Penerbit: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta (1973)
BERISI rangkuman ceramah, diskusi, dan wawancara, buku ini memuat pemikiran Ali Moertopo soal akselerasi pembangunan 25 tahun. Ia menganggap pembangunan dan modernisasi masyarakat seperempat abad setelah kemerdekaan belum juga maksimal.
Ali memaparkan kondisi masyarakat, kekuatan bangsa, dan strategi untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan, menurut dia, berarti perombakan berbagai hambatan kemajuan. Akselerasi pembangunan identik dengan percepatan modernisasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadikan buku ini rujukan untuk menyusun strategi pembangunan jangka panjang.
(22) Manusia dan Kebudayaan di Indonesia Penerbit: Djambatan, Jakarta (1971)
BUKU yang ditulis oleh 13 orang antropolog ini berisi budaya dan adat istiadat pelbagai suku bangsa di Indonesia: Aceh, Nias, Batak, Minangkabau, Jawa, Bali, Kalimantan, Minahasa, Ambon, Flores, Timor, hingga Tionghoa.
Setiap bab menggambarkan satu suku, ditulis seorang ahli dari suku yang sama atau peneliti yang mengunjungi dan meneliti daerah itu.
(23) Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini Penerbit: Alumni, Bandung (1983)
MERUPAKAN kumpulan karangan, pernyataan, dan pidato Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri, buku ini dijadikan pegangan untuk menganalisis pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pergulatan Mochtar memperjuangkan keutuhan teritorial dalam konvensi hukum laut internasional tercatat dalam buku ini. Hasil perjuangan itu sampai kini menjadi sumber hukum kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
(24) Culture and Politics in Indonesia Penerbit: Cornell University Press, London (1972)
UPAYA mengidentifikasi jejak budaya dalam tata politik Indonesia. Para penulisnya mewakili sejumlah ahli antropologi, sejarah, dan ilmu politik. Mereka mengulas cara institusi, kepercayaan, dan nilai-nilai tradisi mempengaruhi kesadaran kekuasaan. Begitu pula pemberontakan, afiliasi politik, yang pada akhirnya membentuk ekspresi budaya baru.
(25) Art in Indonesia: Continuities and Change Penerbit: Cornell University Press, New York (1967)
DALAM buku ini Claire Holt berupaya melacak kontinuitas dan diskontinuitas sejarah kebudayaan Indonesia. Ia menggunakan bahan yang amat luas, mulai data arkeologi sampai relief-relief. Buku ini terdiri atas tiga bagian: warisan, tradisi yang hidup, dan seni modern. Setiap bagian merupakan periode tersendiri dalam sejarah seni Indonesia, dari zaman prasejarah hingga seni rupa Indonesia pada paruh pertama abad ke-20.
Holt (1901-1970) mampu menyajikan argumentasi, ada benang merah yang tak terlihat antara lukisan-lukisan di dinding gua di Pasemah dan lukisan Sudjojono.
(26) Science and Scientists in the Netherlands Indies Penerbit: Board for the Netherlands Indies, Surinam & Curaao, New York (1945)
INILAH buku pepak informasi ilmu alam yang dijadikan panduan ilmuwan Indonesia selepas kemerdekaan. Disusun oleh 75 kontributor, sebagian besar materi sudah pernah dipublikasikan pada 1869-1944. Bentuknya makalah ilmiah, pidato, laporan perjalanan, serta daftar institusi ilmiah dan ilmuwan di Hindia Belanda semasa pendudukan Jepang. Tak kurang dari 134 ilustrasi-foto, sketsa, diagram, dan peta-melengkapi buku ini.
(27) Alam Asli Indonesia: Flora, Fauna, dan Keserasian Penerbit: Yayasan Indonesia Hijau dan Gramedia (1986)
KEKAYAAn flora dan fauna Indonesia dibahas tuntas oleh Kathy MacKinnon, ahli zoologi asal Inggris, dalam buku ini. MacKinnon menelisik keragaman alam Indonesia berdasarkan lokasinya: hutan hujan Kalimantan dan Sumatera, Jawa-Bali, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, serta Papua. Habitat pinggiran semacam bukit kapur, sungai, danau, hutan bakau, tepi pantai, dan karang laut juga dibahas.
MacKinnon mendedikasikan satu bab khusus tentang hubungan manusia Indonesia dengan alamnya. Misalnya bagaimana alam membentuk suku-suku yang berbeda. Kolonialisme dianggap berpengaruh besar karena banyaknya hutan hujan yang beralih menjadi lahan pertanian dan perkebunan.
(28) Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan Penerbit: LP3ES, Jakarta (1981)
MUBYARTO (1938-2005), guru besar Universitas Gadjah Mada, menggagas sistem ekonomi yang mengacu pada etika dan falsafah Pancasila. Sistem ini mengharapkan terwujudnya pemerataan ekonomi dan sosial. Ide utamanya: mendorong para pelaku ekonomi bekerja berdasarkan moral serta mekanisme yang sehat.
(29) NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru Penerbit: LKiS dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994
SEMULA Martin menganggap kaum tradisional sebagai penghambat modernisasi. Setelah mengkaji Nahdlatul Ulama, ia menyimpulkan organisasi "kaum tradisionalis" ini memberikan warna lain dalam proses modernisasi.
Tergambar pula perubahan haluan politik Nahdlatul Ulama: dari semula mengkritik pemerintah, melakukan rekonsiliasi dengan menerima Pancasila sebagai asas tunggal, lalu meninggalkan politik praktis. Sifat paling menonjol dari Nahdlatul adalah sangat terdesentralisasi, yang menggambarkan kemandirian para kiai lokal.
(30) Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban) Penerbit: Yayasan Idayu, Jakarta (1981)
MUNAFIK, segan bertanggung jawab, berjiwa feodal, boros, dan percaya takhayul, tapi berjiwa seni tinggi. Itulah orang Indonesia yang digambarkan buku ini. Naskahnya pertama kali dibacakan Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai ceramah di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 6 April 1977.
Mochtar memaparkan, ciri-ciri itu hasil sekian banyak persinggungan peradaban. Mochtar mengimbau rakyat Indonesia untuk terus mengelola kekayaan nasional, daripada membiarkan diri terbuai jerat kapitalisme.
(31) Catatan Subversif Penerbit: Yayasan Obor Indonesia dan PT Penerbit Gramedia (1987)
INI sebenarnya catatan harian Mochtar Lubis selama sembilan tahun sejak 22 Desember 1956: ketika ia dipenjarakan dan kemudian menjadi tahanan luar. Di situ digambarkan antara lain perilaku elite-elite politik zaman Soekarno dan orang-orang yang dipenjarakan rezim kala itu. Pemimpin Redaksi Indonesia Raya ini juga menulis kasus korupsi pada saat itu.
(32) Pembagian Kekuasaan Negara Penerbit: Aksara Baru (1978)
BERISI teori pembagian kekuasaan negara di Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, serta Indonesia. Buku ini berpengaruh pada proses pembentukan tata negara Indonesia. Pemisahan kekuasaan dalam arti material tak pernah dilaksanakan di Indonesia. Yang ada adalah pemisahan formal.
(33) Laporan dari Banaran Penerbit: Sinar Harapan (1960)
MERUPAKAN memoar Jenderal Simatupang yang dicatatnya selama setahun hingga pengakuan kedaulatan RI, 27 Desember 1949. Di situ diungkapkan peran rakyat dalam perjuangan, termasuk ungkapan Jenderal Sudirman tentang " kemanunggalan rakyat dan tentara". Yang hendak ditonjolkan bukan hanya tentara yang berperan dalam perang rakyat 1945.
(34) Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin Penerjemah: Yusron Asrofie Penerbit: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta (1983)
PROFESOR emeritus Chiba University, Jepang, ini meneliti pergerakan Muhammadiyah di Kotagede, Yogyakarta, 1900-1972. Kotagede dianggap sebagai pusat budaya Jawa yang sinkretis. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam pembaruan ternyata tak bertentangan dengan kebudayaan Jawa. Ini bertolak belakang dengan citra organisasi itu sebagai gerakan pemurnian ajaran Islam. Muhammadiyah justru dianggap terpadu dengan tradisi kejawen dalam menyaring intisari Islam.
(35) Six Decades of Science and Scientists in Indonesia Penerbit: Naturindo, Bogor (2005)
SETELAH 60 tahun Indonesia merdeka, Setijati menggagas buku penerus Science and Scientists in the Netherlands Indies. Pada 2005, berkumpullah 22 peneliti senior, kebanyakan telah pensiun, dan generasi pertama ilmuwan Indonesia. Masing-masing menyusun tulisan dalam bahasa Inggris sesuai dengan bidang keilmuannya.
Beragam topik dalam koridor ilmu alam disajikan, dari geofisika, ilmu tanah, mikrobiologi, ilmu serangga, ornitologi (ilmu burung), nutrisi, kehutanan, pendidikan perbenihan, pengembangan jurnal ilmiah, hingga sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
(37) Pedoman Etik Penelitian Kedokteran Indonesia Penerbit: Fakultas Kedokteran UI (1986)
INI hasil Lokakarya Nasional Etika Penelitian yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 1986. Fakultas itu sebelumnya telah melansir beberapa kode etik penelitian kedokteran, tapi buku ini menjadi rujukan karena disusun dari urun rembuk fakultas kedokteran se-Indonesia.
Meski tipis, buku ini memuat panduan etika penelitian yang padat. Etika penelitian terhadap manusia dan hewan serta penggunaan jenazah diuraikan kerangkanya. Buku ini menyinggung pula etika penulisan ilmiah.
(38) A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia Penerbit: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, Ithaca, New York (1971)LEBIH dikenal sebagai "Cornell Paper", inilah sejarah Gerakan 30 September yang berlawanan dengan versi penguasa Orde Baru. Analisis diambil berdasarkan dokumen Mahkamah Militer Luar Biasa serta artikel-artikel media massa di Jakarta, Medan, Solo, Bali, dan Surabaya pada Oktober-November 1965.
Cornell Paper mengungkapkan, kejadian 30 September 1965 adalah masalah internal Angkatan Darat. Partai Komunis Indonesia justru tidak mengetahui gerakan itu. Naskah yang diedarkan terbatas pada 10 Januari 1966 ini awalnya tanpa nama penyusun. Banyak dikritik karena dianggap kurang akurat, naskah itu langsung memicu perdebatan kalangan intelektual. Identitas penulis akhirnya bocor. Sejak 1968 hingga tumbangnya Orde Baru, Anderson ditolak masuk Indonesia. Pada 1971, edisi revisi naskah itu diterbitkan sebagai buku, lengkap dengan nama penyusunnya.
(39) 125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia 1851-1976 Penerbit: Fakultas Kedokteran UI (1976)
DISUSUN oleh profesor-profesor Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, buku ini merangkum 125 tahun perjalanan pendidikan kedokteran di Nusantara. Pijakan awalnya 1851, ketika Dokter Djawa School, sekolah dokter pertama di Indonesia, didirikan di Jakarta. Penyusun menguraikan perkembangan sekolah dokter pada masa penjajahan Belanda, Jepang, hingga 1976.
Para penulis menyinggung pula kehidupan siswa School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA), cikal-bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Buku ini memuat daftar lulusan pendidikan kedokteran dari zaman Belanda, daftar dokter yang gugur atau hilang semasa perang kemerdekaan, dan statistik mahasiswa kedokteran di Indonesia. l
(40) Ekologi Pedesaan: Sebuah Bunga Rampai Penerbit: CV Rajawali, Jakarta (1982)
BERDASARKAN penguasaan tanah sebagai alat produksi petani, Sajogyo mengelompokkan masyarakat tani sebagai petani atas, tengah, gurem, dan tunakisma. Petani gurem dan tunakisma alias buruh tani merupakan mayoritas masyarakat pedesaan. Tapi mereka tak mendapatkan perhatian politik. Akibat kritiknya, Sajogyo dicopot dari jabatan Ketua Badan Pelaksana Survei Agro-Ekonomi.


















 Mei 19, 2008
Mei 19, 2008
 top
top





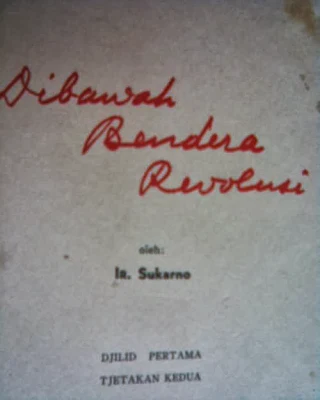



.JPG)







